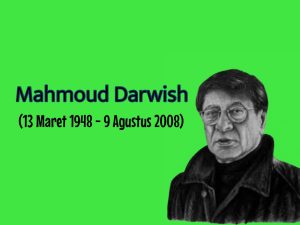
Oleh Fauz Noor
9 Agustus, sembilan tahun yang lalu. Ia pergi, meninggalkan tanah tercinta, bersama ratusan puisi. Puisinya adalah suara Palestina. Penuh duka.
“Kau curi ladang bapaku. Dan tanah tempat kami bercocok tanam. Aku dan seluruh anak-anakku. Dan untukku dan cucu-cucuku. Tak satupun yang kau sisakan. Kecuali batu-batu. Akankah penguasa kalian merenggutnya juga dari kami?”
Kecuali batu-batu. Karena hanya ini senjata orang Palestina. Sementara Israel bersenjata lengkap, bedil, meriam sampai pesawat tempur. Akankah penguasa kalian merenggutnya juga dari kami? Batu adalah jiwa Palestina. Yang dianggap hina, dinjak, diludahi, lalu dibantai.
Kala ia berusia delapan tahun. Pada tahun 1950, ia diminta kepala sekolah untuk ikut perayaan ulang tahun Israel. Ia, murid yang kurus itu, berdiri di muka mikrofon. Dengan bahasa lempeng seorang bocah, ia bersajak tentang seorang bocah Arab yang berseru ke seorang Yahudi, “Kau punya rumah, sedang aku tidak. Kau punya perayaan, sedang aku tidak. Kenapa kita tak bisa bermain bersama?”
Seorang bocah, seringkali lebih memahami kebersamaan. Tapi, apa yang terjadi? Ia ditangkap tentara Israel. Ia pun dicerca dan dihina. “Saya menangis,” pengakuannya dalam buku The Adam of Two Edens, “Bukan karena diriku, tetapil karena mereka menghina bahasa Arab.” Sebagai seorang Muslim, ia mencintai bahasa Arab. Sebagai seorang Arab, ia mencintai bahasa Arab. “Saya pun tak mengerti, kenapa sebuah sajak bisa membuat marah Gubernur Militer,” lanjutnya.
Pada usia 19 tahun, untuk pertama kalinya ia menerbitkan buku kumpulan puisinya berjudul Asfir Bila Ajniha (Burung-Burung Pipit Tanpa Sayap). Satu buku dengan muatan sastra Arab yang tinggi untuk ukuran anak remaja. Disana, emosi menjelma menjadi suara pedih, menggunung dalm pekik protes, walau terus menghantam batu. Ia tak lelah. 30 jilid antologi puisi, 8 jilid kumpulan prosa, adalah karya nyata untuk Palestina.
Ia tahu, bahwa sastra adalah suara, bahwa puisi adalah batas. Batas antara kewarasan dan kegilaan. Ia bisa jadi gila, jika tak bersuara. Dalam puisi pun ia menyuguhkan, batas antara apa yang dikatakan dan yang tak hendak dikatakan. Dan itu semua, untuk tanah tercinta, Palestina.
Sebagai pejuang, tak gentar oleh penjara. Berualang kali ia ditangkap, disiksa, dipenjara. Dengan getir ia menulis, “Aku telah lihat apa yang ingin kulihat tentang penjara.” Ia telah melihat banyak hal: penjara dan pembuangan. Ia berpindah-pindah, ke Moskow, Kairo, Bairut, Paris, dan mati di Rumah Sakit Memorial Herman Hospital di Houston, Texas. “Jadilah engkau ingatan untukku. Agar aku tahu apa yang hilang dalam diriku,” satu cuplikan puisi terakhirnya.
Zionisme adalah nasionalisme yang dibangun dari ingatan, berakar pada khayalan. Jika manusia di Amerika, Rusia, Prancis, India, Indonesia membangun nasionalisme dengan melupakan ikatan-ikatan primordial. Indonesia upamanya, melupakan sunda, jawa, bugis, batak, dan yang lainnya. Israel membangu nasionalisme dari Kitab Suci yang dikhayalkan, “tanah yang dijanjikan”. Israel memegang kuat pikiran kampungan bahwa primordialitas ke-Yahudi-an adalah “umat pilihan Tuhan”. Sedang Palestina, seperti nation-nation lainnya, membuang primordialitas untuk membangun ingatan, bukan tentang agama atau etnis leluhur, tapi tentang tanah kelahiran yang tak ada lagi. Padahal, seperti dalam satu penggalan puisinya, “Tanah, seperti bahasa, ia punya pewaris.”
Ialah Mahmoud Darwish, pejuang Palestina yang tak lelah bersuara, bersyair, lewat puisi dan prosa. Dan siapa pun tahu, istiqamah adalah bajunya para jawara. Berulang kali ia ditawari untuk berkhianat jadi penjilat, “Rakyat Palestina terlalu miskin untuk menjadi tambah miskin,” jawabnya. Mahmoud Darwish adalah jawara, itu sebabnya mati dengan nama mulia.
Ribuan rakyat Palestina tunduk kepala, kala Darwish tiada. Tapi, jiwa Darwish pasti kuat di sukma mereka. Hanya satu, Palestina merdeka. Untuk Mahmoud Darwish dan Palestina, al-Faatihah [ ]
7 Agustus 2017 (Kolom Marginalia)
